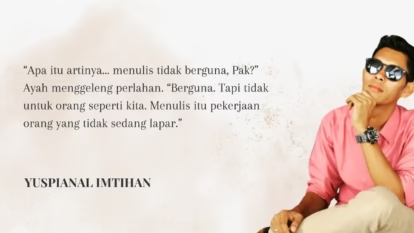“Ramlah? Apa yang sedang kamu kerjakan?”
Di setiap penjuru berserakan kertas berisi tulisan-tulisan yang belum rampung. Ada beberapa kertas dengan tulisan yang sudah tidak terbaca. Bekas disobek. Juga beberapa yang luntur terkena air. Entah bekas air apa. Kali ini aku terpaksa harus menuduh air hujan yang membasahinya. Meskipun aku tahu kalau itu bekas air mata Ramlah. Masih ada sisa air mata yang belum kering di pipinya. Walau dia sudah berkali-kali mengusap dengan tangannya sambil mengendus. Ia spontan melakukannya ketika aku tiba-tiba membuka pintu kamar.
“Tidak ada, aku hanya sedang butuh sendiri”, jawabnya dengan singkat.
Kamu tidak keluar selama empat waktu. Itu membuat ibu khawatir. Kalau ada masalah silakan cerita. Jangan pendam sendiri. Karena kamu tidak pernah sendiri.
“Sudah aku katakan tidak ada masalah serius, aku minta maaf”
“Sebentar lagi malam, bantu ibu memasukkan tenunannya”
“Bukannya setiap hari tidak pernah dimasukkan?”
Setiap harinya penenun di sini memang tidak pernah memasukkan tenunannya ketika malam tiba. Akan tetapi ada yang berbeda sejak beberapa minggu terakhir. Penenun tidak berani meninggalkan tenunannya di luar rumah ketika malam hari. Sore ini langit memang terlihat mendung. Tapi bukan itu alasannya. Mereka tidak sedang takut tenunnya basah diguyur hujan. Ada masalah lain. Sepele tapi bisa saja menjadi masalah yang serius.
“Sekarang harus dimasukkan!”
“Kenapa?”
“Simpan dulu pertanyaanmu sebelum matahari semakin tenggelam. Ibu sudah menunggu di teras”
Tidak kurang sejak sebulan yang lalu. Banyak penenun risi dengan kehadiran beberapa orang dari luar. Tidak ada yang tahu pasti tujuan mereka. Gelagat mereka biasa saja. Tapi sejak dua minggu yang lalu ada beberapa alat tenun yang hilang. Bagi penenun, alat tenun sudah menjadi bagian dari diri mereka.
Penenun tidak menuduh orang tak dikenal itu pencurinya. Hanya sedang waspada. Berusaha untuk menjaga harta mereka. Bagi sebagian orang tenun merupakan produk tidak bernilai. Tapi bagi penenun di desa kecil ini. Tenun merupakan harta mereka. Ibuku juga merupakan seorang penenun. Entah sudah generasi yang ke berapa. Yang jelas nenek dan buyutku dan terus ke generasi di atasnya juga merupakan penenun yang ulung.
Sebentar, aku ingin sedikit bercerita dalam cerita ini. Beberapa tahun yang lalu.Ada seseorang dari luar desa kecil ini datang ke rumah kami. Untuk membeli kain tenun. Namanya Pak Darun. Datang seorang diri ketika ibuku sedang menenun.
Saat itu ibuku dengan ramah menjamu tamu. Bukan sedang mencuri hati calon pelanggannya. Tapi memang itulah warisan sederhana dari nenek moyang. Tetap ramah dengan siapa pun. Terlepas dari momen itu akan ada proses transaksi atau tidak. Sudah menjadi tabiatnya ramah menjamu tamu.
Kemudian setelah melihat rangkaian proses lahirnya sebuah kain tenun. Pak Darun menanyakan harga kain tenun yang menggantung pada tali yang membentang di tiang teras.
“Yang itu harganya berapa?” ucap Pak Darun sembari menunjuk kain tenun yang menarik perhatiannya.
“Bapak sedang terburu-buru?”, tanya ibuku dengan ramah.
“Tidak juga, saya hanya ingin tahu harganya”
“Kalau boleh, saya ingin ceritakan tentang kain tenun itu”
Ibuku mulai menceritakan tentang kain tenun yang dipegang Pak Darun. Kain yang sedang diceritakan namanya ragi (motif) Pucuk Rebung. Ia bercerita kalau kain itu bukan sebuah produk semata. Tapi punya cerita atau filosofi.
Seperti tarian tangan pelukis dengan kuasnya di atas kanvas. Pelukis merupakan seniman. Penenun juga merupakan seorang seniman. Yang membedakannya hanya media, penenun melukis melalui proses silang benang lungsin dengan benang pakan. Sekian banyak proses penyilangan benang yang kemudian melahirkan ragi Pucuk Rebung dan reragian lainnya
Saat itu, sambil menikmati kopi yang dibuatkan oleh Ramlah. Pak Darun dengan seksama mendengar cerita ibuku. Ibuku menceritakan bahwa ragi Pucuk Rebung terinspirasi dari tunas bambu yang baru tumbuh. Melambangkan kehidupan. Proses pertumbuhan bambu muda hingga tua melambangkan manusia yang bermanfaat. Rebung yang baru tumbuh masih terbungkus dengan kelopak yang memiliki bulu halus. Seperti halnya bayi baru lahir yang harus dirawat dengan baik.
Di saat ibuku menjelaskan filosofi ragi Pucuk Rebung. Ramlah dimintanya untuk ikut mendengarkan. Padahal saat itu Ramlah sedang melanjutkan tenunannya. Tepat ketika Ramlah sudah duduk di sebelahnya. Ibuku lanjut menjelaskan Pak Darun. Menjelaskan pertumbuhan rebung dengan batang yang lurus mengibaratkan perjalanan manusia yang harus taat pada perintah Tuhan. Lalu bambu dewasa akan memiliki ujung yang melengkung ke bawah dan punya daun yang rimbun. Begitu juga manusia yang sudah akil balig harus bertanggung jawab dengan diri sendiri dan lingkungannya.
Aku masih ingat saat Pak Darun datang, aku baru saja pulang dari rumah nenek. Saat aku baru datang, ibuku memperkenalkan namaku ke Pak Darun. Kemudian setelah berbasa-basi sebentar. Ramlah mengatakan kalau bambu akan semakin kuat ketika sudah semakin tua. Aku yang baru pulang heran, belum tahu obrolan mereka. Juga bingung kenapa topik pembicaraan mereka soal bambu. Aku tidak meluapkan keherananku dengan pertanyaan. Masih diam mendengar Ramlah melanjutkan perkataannya. Dia mengatakan bambu yang kuat dan ujung yang lengkung menyiratkan makna bahwa manusia harus senantiasa rendah hati. Meskipun memiliki ilmu yang banyak. Seorang manusia tidak boleh lupa dengan asalnya.
Cerita panjang dari ibuku. Membuat Pak Darun tersenyum. Paham dengan semua yang dikatakan lawan bicaranya. Ia sadar sedang berbicara dengan seorang seniman dan karyanya. Ternyata Pak Darun seorang budayawan. Punya pemahaman budaya yang luas, salah satunya budaya menenun.
Pertanyaannya soal harga kain tenun bukan untuk sekedar tahu nominal harga. Tapi ada tujuan lain. Aku ingat betul ketika dia menceritakan latar belakangnya. Dia hanya tersenyum dan santai mengenalkan dirinya.
“Sangat di sayangkan sebagian besar penenun di desa ini hanya sebagai robot produksi saja. Tidak sadar mereka seniman”, katanya dengan menghela nafas.
Tidak bisa disangkal. Perkataan Pak Darun beberapa tahun yang lalu itu barangkali ada benarnya. Banyak dari penenun di sini memang belum paham nilai dari karyanya. Mereka mematok nilai hanya dari nominal harga di pasar. Entah siapa yang memulai doktrinnya. Peran pemerintah juga belum terlihat jelas untuk mengatur harga dan mencari pasar yang tepat untuk penenun. Seingatku, dulu ketika Pak Darun ke rumah. Sebelumnya dia sudah mampir ke rumah penenun yang lain. Katanya dia membeli kain tenun di beberapa tempat. Ragi dan jenis bahan yang sama. Tapi katanya harganya berbeda.
Pernah beberapa kali diadakan diskusi untuk mencari titik tengah agar harga kain tenun sama di setiap tempat. Waktu itu dihadiri tokoh pemuda, penenun, dan pihak pemerintah. Pemerintah yang punya kuasa, menjanjikan untuk segera menemukan solusi yang tepat terkait masalah itu. Tapi hingga sekarang sudah beberapa kali ganti pemimpin belum terealisasi. Satu-satunya yang terealisasi cuma dasi kupu-kupu yang digunakan. Sekarang sudah menggunakan motif kain tenun. Entah itu sebuah kabar baik atau buruk.
Azan magrib sudah selesai dikumandangkan. Setelah menunaikan perintah. Aku yang masih menggunakan sarung tengah duduk santai di berugak. Tidak lama kemudian Ramlah memanggilku untuk makan. Tiba di dapur Ramlah terlihat sedang menggelar tikar di lantai. Sekarang kami makan bertiga saja. Karena sejak Ramlah kelas dua SMA dan aku memasuki semester empat di kuliahku, ayahku pergi merantau ke Malaysia. Sekitar satu tahun yang lalu.
Selesai makan aku penasaran kenapa Ramlah menangis tadi sore. Kemudian aku menanyakannya ketika masih di posisi bersila. Sambil memakan sisa kerupuk udang yang belum habis di piringku.
“Gimana Ramlah, sudah selesai dengan dirimu?” tanyaku pada adikku satu-satunya.
“Sudah kelar semua, kecuali tulisan itu”
“Kenapa nangis, patah hati dengan laki-laki?”, ucapku menggoda.
“Maaf yaa, air mataku terlalu berharga untuk menangisi laki-laki”
“Terus kenapa bendungan kuat itu tidak mampu membendungnya?”
Ramlah tidak menjawab pertanyaanku. Ia memilih untuk berdiri membantu ibu mencuci piring. Aku penasaran dengan kertas berisi tulisan-tulisan yang berantakan tadi. Memutuskan untuk melihat di kamarnya. Masih tetap berantakan ternyata. Aku memungut beberapa tulisan. Ada beberapa gambar yang belum usai. Terlihat seperti sebuah desain busana. Dari sekian banyak kertas. Aku mengambil tulisan yang sepertinya belum rampung. Sebuah puisi. Ramlah memberinya judul “Sampai Kapan Perempuan Akan Mengikat Diri Dalam Ketukan”. Rasa penasaranku semakin menjadi jadi. Aku mencoba untuk memahami tulisan Ramlah. Dengan seksama aku baca setiap penggalan kata yang digunakan.
Sebuah kehormatan menjadi seorang perempuan penjaga tradisi
Mengabdi untuk setiap irama ketukan
Dan di antara jalinan benang
Aku seolah berada di atas panggung untuk berpuisi
Membacakan diksi-diksi klasik yang telah ratusan tahun terwariskan
Secara tidak langsung dan terlambat aku sadari
Penonton yang menyaksikan juga berasal dari lintas masa
Sampai kapan pertunjukan ini akan berlangsung
Portal waktu tidak mampu membuat kita abadi
Kain tenun adalah sebuah tongkat estafet yang harus terus digenggam
Dan lalu, jika ada di antara kita
Hanya sekedar menyimpan tongkatnya dalam peti
Kemudian menempatkannya tepat di atas lemari
Atau bahkan di bawah ranjang tempatmu biasa menari
Kau tahu?
Sejatinya kita sudah lama di mata-matai
Mereka semua telah lama bersiap untuk mengambil alih pertunjukan
Jika demikian sampai kapan kita akan menunggu?
Harapan-harapan itu adalah penantian panjang yang sedari lama sudah berdebu
Realisasi janji dengan sebuah dasi berkedok inovasi
Itu semua hanyalah improvisasi agar mereka tidak kita caci
Jangan katakan sepenggal kalimat suci itu sekadar kumpulan diksi
Sebab kita adalah kain tenun itu
Genggaman satu sama lain
Juga saling…
– Malang, 1 Januari 2024
Penulis : Ahmad Rijal Alwi, anggota Pringgasela Literasi.