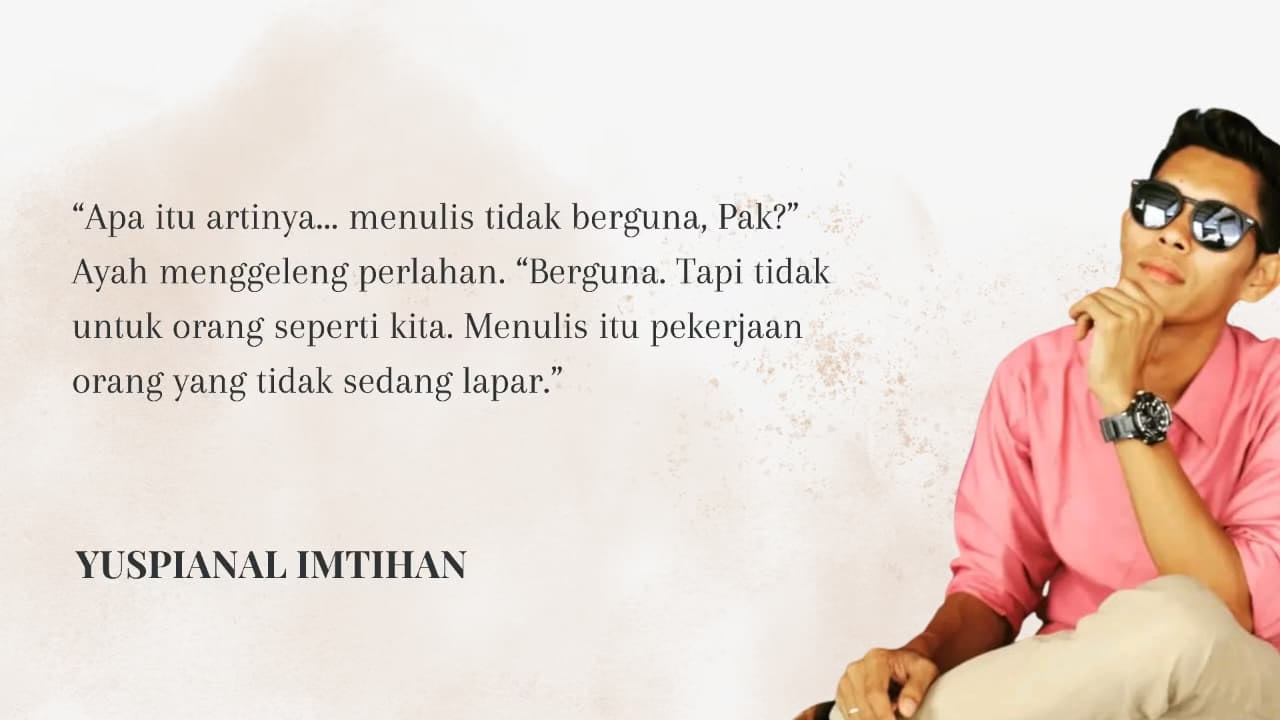Di kota yang malamnya selalu gelagapan oleh sirine, suara seorang lelaki setengah uzur kembali mengembara. Ia bergerak dari satu telinga ke telinga lain, seakan ingin memastikan bahwa dirinya masih didengar. Di tepi Sungai Sanggeng yang airnya membawa bau botol-botol pecah dan warna-warna muram dari sisa pesta yang tak pernah ia hadiri, Paman Riber dengan wajah ungu seperti habis dipukul, kembali menegakkan tubuhnya. Malam itu ia memanggil para pemuda yang sengaja menjauh dari urusan sekolah, memisahkan diri dari segala bentuk rapor, nilai, dan ruang kelas yang menua di Jeranjang, Kabupaten Pangea.
Seperti biasa, ia membuka pertemuan dengan pertanyaan yang baginya penting, namun bagi mereka mungkin hanya angin lewat.
“Apa makna filsafat pendidikan yang kalian pahami?” katanya.
Pertanyaan itu jatuh, tetapi tak ada yang menangkapnya. Keheningan mengeras. Para pemuda itu menunduk, atau memandang gelap sungai, atau sekadar menunggu malam selesai. Mereka pernah duduk di bangku sekolah, tetapi bangku itu telah lama mereka tinggal. Sejak SD, mereka memilih pergi. Dunia belajar bukan rumah bagi mereka.
Melihat tak ada jawaban, Paman Riber berdiri perlahan bagai sebuah tiang tua yang memaksa dirinya tegak, lalu memulai orasinya seperti malam-malam sebelumnya.
“Beginilah jadinya kita!” Serunya. “Pendidikan kita tercabik, digiring entah ke jurang apa. Para cendekiawan yang katanya lahir beribu-ribu itu hanya diam. Seperti sedang dikutuk menjadi batu. Ilmu pengetahuan kita hilang, seperti terbawa angin yang malas kembali.”
Ia mengepalkan tangannya seakan memegang petir yang retak di langit. Kata-katanya memercik. “Hai kalian, penghuni tanah yang berdebu dan berapi! Serendah inikah kita sebagai makhluk yang diberi akal?” Para pemuda itu tetap diam. Paman Riber terus menembakkan kata-kata. Kata yang panjang, pahit, dan kadang terlalu besar untuk mulutnya sendiri. Sampai akhirnya ia kalah. Bukan oleh argumen, melainkan oleh usia, juga oleh waktu yang tiba-tiba berubah menjadi subuh. Rumahnya hanya beberapa langkah dari dasar sungai itu, tetapi perjalanan pulang selalu terasa jauh setelah sebuah pidato yang tak pernah didengar.
Paman Riber sudah lama tahu: tak satu pun dari mereka mau digurui. Ia pernah berangan-angan menjadi panutan, namun ia sudah mengubur angan itu. Yang tersisa hanyalah keinginan agar mereka, suatu saat, pikirannya bergerak meski sedikit saja.
Ia sering melakukan pertemuan seperti itu. Di kota-kota yang ia lewati, ia membawa dirinya seperti buku tua yang wajib dibacakan kepada siapa pun yang ditemuinya. Jika ia melihat orang-orang duduk dalam lingkaran sambil menenggak minuman murah, ia merasa wajib berbicara. Baginya, keheningan orang lain adalah undangan. Ia mengira dirinya seperti cip komputer berisi miliaran data, padahal kadang ia hanya lelaki kesepian yang takut ilmunya mati sendirian.
Hari itu, kejanggalan besar terjadi. Awan hitam menggulung di hulu sungai. Tak ada tanda hujan, tetapi air bah tiba-tiba datang, liar, memecah rumah-rumah yang berdiri di sepanjang jalurnya. Rumah Paman Riber, yang dibangun dengan pilar kokoh, hanyut, retak, patah, lalu hilang. Sapi, kambing, ayam, juga itik-itiknya lenyap ditelan arus.
Ia tak menangisi hewan-hewan itu. Tidak juga uang atau barang-barang yang hilang. Yang ia ratapi adalah ijazah-ijazahnya, piagam yang ia kumpulkan sejak kecil, lencana kehormatan yang tidur bersama ingatannya. Semua hanyut. Seakan kepalanya ikut hanyut. Ia merasa kosong, seperti lemari yang baru dirampok. Kesedihan itu menggerogoti dirinya dan keluarganya. Mereka selamat dari banjir, tetapi tak sepenuhnya selamat dari luka yang ditinggalkannya.
*
Di Kota Mataram yang malamnya selalu terdengar seperti rintihan panjang yang tak selesai, seorang anak pemulung berdiri di atas tumpukan sampah. Namanya Abigail. Usianya belum genap dua belas tahun, tetapi matanya telah memiliki kedalaman yang biasanya hanya dimiliki oleh orang dewasa yang gagal menua dengan baik.
Tumpukan sampah itu berada persis di belakang salah satu kantor pemberitaan. Tempat di mana berita berita lahir, namun juga tempat di mana banyak mimpi orang dikubur begitu saja tanpa nisan. Di sana, di antara plastik lusuh dan kertas-kertas lembap, Abigail menemukan beberapa lembar cerita pendek: potongannya terpisah, beberapa kalimatnya patah, seperti tubuh kehilangan tulang.
Ia sudah selesai membacanya dengan diam yang sungguh-sungguh. Sekitar lima menit.
Hingga suara ayah memanggilnya dari kejauhan. “Hei, Nak! Apa itu? Uang?” suara ayah, serak dan tebal, lebih mirip gema dari seseorang yang telah terlalu lama menahan kecewa.
Abigail menggeleng. “Cerita pendek, Pak. Tapi sialnya… belum selesai.”
Ayah mendekat, menyingkirkan beberapa karung sampah dengan gerakan yang seperti menyingkirkan harapan-harapan kecil. Ia membaca sepintas, matanya mengerut, lalu tanpa ragu mendorong lembaran cerita itu masuk ke keranjang.
“Pengarang amatiran. Lihat? Macet. Tersendat. Nggak selesai. Begitulah nasib kebanyakan yang mencoba jadi penulis.”
Abigail menatapnya lebih lama dari biasanya. “Pak… kalau aku besar nanti, aku ingin jadi pengarang. Boleh ya?”
Ayah tertawa lirih, seperti seseorang yang mencoba menertawakan rasa sakit dan gagal. “Jangan, Nak.”
“Kenapa? Apa salahnya jadi pengarang?”
Ayah diam sesaat. Ia memungut penutup botol, memasukannya ke karung, lalu menjawab pelan namun tajam.
“Menjadi pengarang itu pekerjaan orang yang punya cukup waktu untuk patah hati, cukup uang untuk tetap makan, dan cukup kebodohan untuk percaya bahwa kata-kata bisa mengubah hidup. Kita tak punya ketiganya.”
Abigail menelan ludah. Entah kenapa tiba tiba ayah semakin memperbesar volume suaranya. Seolah ia ingin dunia dan seisinya tahu. “Tapi kan bapak suka menulis dulu…”
“Dulu. Bukan sekarang.”
Ia menunjuk kantor berita di belakang mereka. “Dari kantor itulah Bapak berhenti berharap. Setiap hari Bapak melihat naskah orang-orang yang menunggu, orang yang percaya dibuang tanpa dibaca. Mereka menaruh hidupnya di atas kertas, tapi kertas itu cuma mampir sebentar sebelum jadi sampah.”
“Apa itu artinya… menulis tidak berguna, Pak?”
Ayah menggeleng perlahan. “Berguna. Tapi tidak untuk orang seperti kita. Menulis itu pekerjaan orang yang tidak sedang lapar.”
Abigail menggigit bibirnya, menahan sesuatu yang sulit ia jelaskan. “Tapi… aku merasa kalau baca cerita itu… aku hidup dua kali, Pak. Aku merasa seperti bisa melihat sesuatu yang tidak ada di dunia ini. Apa itu salah?”
Ayah menatapnya lama. Sebuah tatapan yang hampir rapuh, hampir kalah.
“Tidak salah. Tapi berbahaya. Imajinasi itu seperti angin. Dan kita ini rumah-rumah tanpa atap. Begitu angin masuk, semuanya mudah roboh.”
Abigail mendesah. “Kalau begitu… apa gunanya aku sekolah, Pak? Kalau aku tidak boleh bermimpi?”
Ayah terdiam. Pertanyaan itu mengenai dirinya seperti sebilah pisau yang telah lama menunggu untuk ditarik dari balik punggung. Ia akhirnya duduk di tepi trotoar, memandang karung sampahnya sendiri seolah dari karung itu keluar seluruh masa lalunya.
“Nak…dulu Bapak menulis karena ingin punya suara. Tapi suara itu tidak pernah didengar. Sampai akhirnya Bapak sadar, suara yang tidak didengar itu menyakitkan.”
Ia menunjuk karungnya.
“Lihat. Sampah sampah ini tidak pernah mengecewakan Bapak. Sampah ini justru selalu jelas takdirnya. Berbeda dengan cita-cita.”
Abigail menunduk, dan suaranya keluar pelan-pelan. “Tapi Pak… kalau semua orang berhenti berharap… apa tidak semakin gelap dunia ini?”
Ayah terdiam. Kalimat itu kini berbalik menusuknya. Ia tak punya jawaban lain selain kejujuran yang paling pahit. “Kadang, Nak… menerima gelap lebih mudah daripada menyalakan lampu yang tak pernah punya listrik.”
Ada jeda. Jeda yang dingin. Sampai akhirnya Abigail berbisik, “Pak… orang berkacamata itu dari tadi memperhatikan kita.”
Ayah menoleh. Tetapi tak bereaksi. Ia kemudian menarik tangan Abigail dan mendekati lelaki itu.
“Miq Tuan… Ini anak saya, Abigail. Katanya ia ingin jadi pengarang. Seperti pelungguh.” Lelaki berkacamata itu berdiri di teras rumah kumuh yang halaman depannya ditelan semak. Di dindingnya ada papan kecil bertuliskan: AKAR POHON.
Lelaki itu menatap Abigail lama. Sangat lama. Seolah ia sedang mempertimbangkan nasib dunia. Tapi ia tak berkata apa-apa. Hanya senyum kecil yang samar. Senyum yang bisa berarti dua hal: restu atau ironi. Gerbang besi rumah itu terbuka sedikit. Cukup untuk membuat udara berubah aneh. Abigail merasa takut. Bukan kepada lelaki itu. Melainkan kepada kemungkinan baru yang menunggu diujung. Bahwa mimpinya mungkin benar-benar bisa dimulai atau dimatikan di rumah itu. Ia menarik tangan ayah. Memilih pergi. Ayah menunduk. Abigail menoleh sekali lagi. Lelaki itu masih berdiri di sana, seperti penjaga sebuah dunia yang hanya dibuka untuk orang-orang yang berani masuk dan hancur. Dan Abigail belum tahu apakah ia siap untuk itu.
Bersambung…